Tahukah kamu bahwa masalah sosial yang diabaikan pemerintah semakin menggunung di 2025? Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan ekstrem masih menyentuh 9,03 juta jiwa per September 2024, sementara isu kesehatan mental remaja meningkat 34% sejak pandemi menurut Kementerian Kesehatan. Fakta mengejutkan lainnya: 1 dari 3 pekerja muda mengalami underemployment, namun solusi konkret masih minim.
Di tengah hiruk-pikuk pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, ada banyak masalah sosial yang diabaikan pemerintah dan terselip di balik narasi kemajuan. Gen Z sebagai generasi yang paling terdampak perlu tahu isu-isu krusial ini agar bisa mengadvokasi perubahan.
Daftar Isi:
- Krisis Kesehatan Mental Generasi Muda yang Terabaikan
- Masalah Akses Pendidikan Berkualitas di Daerah Terpencil
- Isu Lapangan Kerja Layak untuk Fresh Graduate
- Problem Perumahan Terjangkau di Kota Besar
- Ketimpangan Akses Layanan Kesehatan Dasar
- Polusi Udara dan Dampak Kesehatan Jangka Panjang
- Kekerasan Berbasis Gender yang Terus Meningkat
1. Krisis Kesehatan Mental Generasi Muda yang Terabaikan
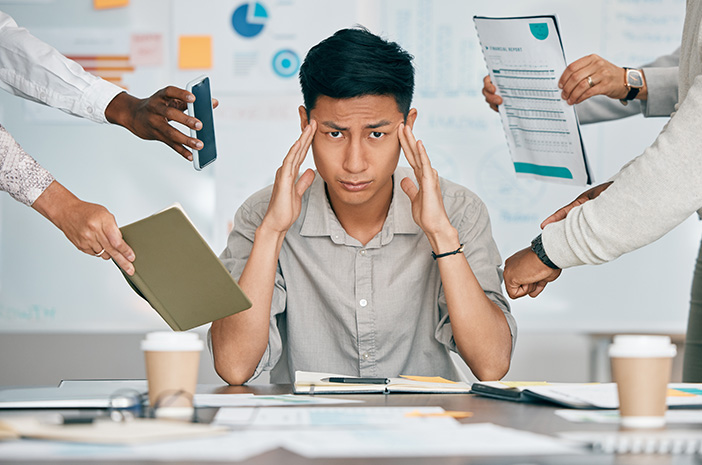
Masalah sosial yang diabaikan pemerintah paling mendesak di 2025 adalah kesehatan mental anak muda. Data Kemenkes menunjukkan 15,5 juta remaja Indonesia (usia 15-24 tahun) mengalami gangguan kecemasan dan depresi, namun hanya 9% yang mendapat akses layanan psikolog profesional.
Sistem BPJS Kesehatan masih sangat terbatas untuk layanan psikiatri—rata-rata waktu tunggu konsultasi mencapai 3-6 bulan di rumah sakit pemerintah. Padahal, WHO menetapkan rasio ideal 1 psikolog untuk 30.000 penduduk, sementara Indonesia baru mencapai 1:200.000.
Contoh nyata: Mahasiswa di Jakarta bernama Rina (23) harus menunggu 4 bulan untuk konsultasi pertama di puskesmas, akhirnya memilih layanan swasta yang menghabiskan Rp800.000 per sesi—setara 40% UMP DKI. Tanpa intervensi sistematis, WHO memproyeksikan kerugian ekonomi akibat produktivitas menurun mencapai Rp385 triliun pada 2030.
Fakta Penting: Indonesia mengalokasikan hanya 1% dari total budget kesehatan untuk kesehatan mental, jauh di bawah standar WHO yang merekomendasikan 5-10%.
2. Masalah Akses Pendidikan Berkualitas di Daerah Terpencil

Kesenjangan kualitas pendidikan antara Jawa dan luar Jawa masih menjadi masalah sosial yang diabaikan pemerintah secara serius. Data Kemendikbudristek 2024 mencatat 47.000 sekolah di Indonesia kekurangan guru berkualitas, dengan 63% berada di Papua, Maluku, dan NTT.
Skor PISA 2023 Indonesia menunjukkan siswa di Jakarta unggul 127 poin dibanding Papua dalam literasi membaca—gap terbesar dalam sejarah penilaian pendidikan nasional. Akses internet untuk pembelajaran daring juga timpang: 89% siswa Jakarta punya akses stabil vs hanya 23% di kabupaten terluar.
Kasus di Kabupaten Nduga, Papua: sekolah SD dengan 180 siswa hanya memiliki 4 guru tetap, sehingga sistem pembelajaran multigrade (1 guru mengajar 3 kelas berbeda) menjadi norma. Program Guru Garis Depan yang dijanjikan sejak 2022 baru terisi 34% dari target, dengan dropout rate guru mencapai 58% dalam tahun pertama.
Dampak jangka panjangnya? Riset Smeru Institute menunjukkan anak dari daerah terpencil memiliki probabilitas 4,7 kali lebih kecil untuk masuk perguruan tinggi berkualitas dibanding anak dari kota besar. Analisis mendalam tentang kesenjangan pendidikan menunjukkan bahwa tanpa reformasi distribusi guru, gap ini akan melebar hingga 2035.
3. Isu Lapangan Kerja Layak untuk Fresh Graduate

Masalah sosial yang diabaikan pemerintah berikutnya adalah krisis pekerjaan layak untuk lulusan baru. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan universitas mencapai 5,83% (Februari 2025), tertinggi sejak 2019. Yang lebih mengkhawatirkan: 41% fresh graduate bekerja di posisi yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka.
Fenomena “gig economy” yang eksploitatif meningkat pesat—67% pekerja digital di bawah 25 tahun tidak punya jaminan sosial, cuti sakit, atau kontrak jelas. Platform ride-hailing dan delivery memang menyerap tenaga kerja, tapi survei LIPS UI 2024 menunjukkan 78% driver ojol berpendidikan S1 dengan penghasilan rata-rata Rp2,8 juta/bulan—jauh di bawah UMP.
Take contoh Budi (24), lulusan Teknik Informatika yang bekerja sebagai content moderator dengan upah Rp4,5 juta tanpa tunjangan. Skill coding-nya tidak terpakai, dan perusahaan outsourcing tempatnya bekerja tidak menawarkan program pelatihan. Kemenaker mencatat hanya 23% perusahaan besar punya program upskilling sistematis untuk karyawan junior.
Data LinkedIn Workforce Report Indonesia 2025 menunjukkan mismatch antara skill yang diajarkan kampus dengan kebutuhan industri mencapai 64%—tertinggi di ASEAN. Pemerintah menargetkan program vokasi-link and match, namun implementasinya baru 18% dari rencana.
4. Problem Perumahan Terjangkau di Kota Besar

Krisis perumahan adalah masalah sosial yang diabaikan pemerintah yang semakin akut di 2025. Bank Indonesia melaporkan backlog perumahan nasional mencapai 12,7 juta unit, sementara harga properti di Jakarta, Surabaya, dan Bandung naik rata-rata 8,3% per tahun—dua kali lipat inflasi umum.
Gen Z yang baru mulai bekerja hampir mustahil membeli rumah: rasio harga rumah terhadap pendapatan tahunan (housing affordability) di Jakarta mencapai 15:1, artinya butuh 15 tahun gaji tanpa pengeluaran untuk beli rumah tipe 36. Bandingkan dengan standar WHO yang menyebut sehat di angka 3-5:1.
Program sejuta rumah pemerintah terkendala target market yang meleset—85% unit terbangun berada di lokasi pinggiran tanpa akses transportasi publik memadai. Survei Kompas 2024 menunjukkan hanya 12% pembeli rumah subsidi yang benar-benar MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), sisanya dibeli spekulan.
Data Mengejutkan: 34% anak muda usia 25-34 tahun di Jabodetabek masih tinggal dengan orangtua karena tidak mampu sewa atau beli properti sendiri—naik dari 21% di 2019.
Sementara itu, kost-kostan dan kontrakan dengan harga Rp2-4 juta/bulan di area strategis semakin langka. Pemerintah belum punya kebijakan komprehensif untuk rent control atau social housing yang efektif, berbeda dengan Singapura atau Vietnam yang sukses dengan model HDB dan low-cost apartment.
5. Ketimpangan Akses Layanan Kesehatan Dasar

Meski BPJS mengklaim cakupan universal, masalah sosial yang diabaikan pemerintah dalam hal akses kesehatan masih massif. Data Kemenkes 2024 mencatat 185 kabupaten/kota kekurangan dokter spesialis, dengan rasio 1:47.000 penduduk di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
Waktu tunggu operasi non-darurat di RSUD provinsi luar Jawa mencapai 6-14 bulan, memaksa pasien mencari rumah sakit swasta atau membiarkan penyakit memburuk. Contoh: Ibu Siti di Lombok harus menunggu 9 bulan untuk operasi tumor jinak, akhirnya meminjam Rp35 juta untuk operasi di RS swasta Bali.
Kesenjangan infrastruktur juga parah—Jakarta punya 1 tempat tidur RS per 500 penduduk, Papua 1:2.800 penduduk. Pandemi memperparah situasi: 412 puskesmas tutup permanen akibat defisit anggaran, dan 28% tenaga medis di daerah rural mengundurkan diri mencari posisi lebih baik di kota.
Program Nusantara Sehat yang bertujuan menempatkan tenaga kesehatan di daerah sulit hanya terisi 41% dari kuota 2025. Insentif finansial tidak menarik (Rp7,5 juta/bulan untuk penempatan ekstrem), sementara biaya hidup di daerah terpencil justru lebih tinggi karena logistik.
Riset Mahkamah Agung 2024 mencatat ada 1.247 gugatan malpraktek terkait keterlambatan penanganan—naik 67% dari 2020. Mayoritas kasus terjadi karena rujukan terlambat atau faskes tingkat pertama tidak mampu diagnosis tepat.
6. Polusi Udara dan Dampak Kesehatan Jangka Panjang

Masalah sosial yang diabaikan pemerintah yang berbahaya namun invisible adalah polusi udara. IQAir 2024 menempatkan Jakarta sebagai kota dengan kualitas udara terburuk ke-3 di Asia Tenggara, dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 38,2 µg/m³—hampir 8 kali lipat standar WHO (5 µg/m³).
Dampak kesehatannya nyata: Kemenkes memproyeksikan 38.000 kematian prematur per tahun akibat penyakit respiratori terkait polusi, dengan kerugian ekonomi Rp58 triliun dari biaya kesehatan dan produktivitas hilang. Anak-anak paling rentan—riset IDAI menunjukkan 62% anak Jakarta mengalami gangguan fungsi paru ringan hingga sedang.
Pemerintah DKI menjalankan program ganjil-genap dan uji emisi, tapi pengawasan lemah—hanya 34% kendaraan yang patuh uji emisi rutin. Pembakaran sampah ilegal di TPA dan aktivitas industri tanpa AMDAL juga masih marak tanpa enforcement berarti.
Yang lebih parah, tidak ada sistem peringatan dini polusi untuk masyarakat. Berbeda dengan Bangkok atau Beijing yang punya app real-time air quality, Indonesia baru mulai memasang 50 sensor ISPU pada 2024—jauh dari kebutuhan minimal 500 sensor untuk monitoring efektif di Jabodetabek.
Komitmen mengurangi emisi 29% (NDC) pada 2030 terancam gagal—realisasi 2024 baru 11%. Transisi ke energi bersih berjalan lambat: pangsa PLTU batubara masih 60% dari total pembangkit listrik nasional.
7. Kekerasan Berbasis Gender yang Terus Meningkat
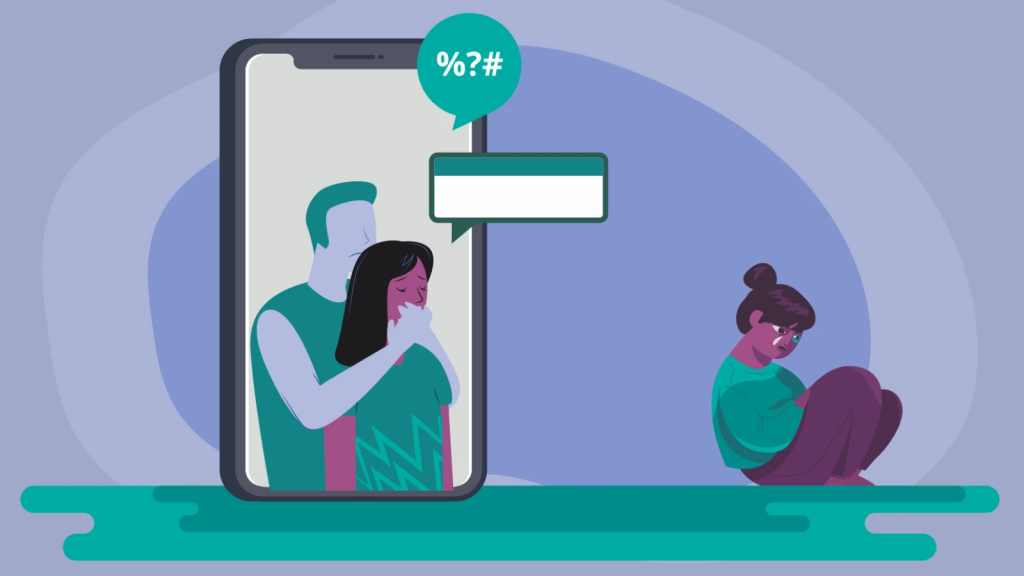
Masalah sosial yang diabaikan pemerintah terakhir namun sangat krusial adalah kekerasan berbasis gender (KBG). Komnas Perempuan mencatat 467.398 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2024—naik 21% dari tahun sebelumnya. Yang dilaporkan ini hanya puncak gunung es, estimasi kasus sebenarnya 7-10 kali lipat.
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mendominasi dengan 71% kasus, diikuti kekerasan seksual 18%, dan trafficking 11%. Yang mengkhawatirkan: 64% korban tidak melaporkan ke pihak berwajib karena stigma sosial, ketidaktahuan prosedur, atau takut reviktimisasi oleh sistem hukum.
Sistem perlindungan korban masih sangat lemah—hanya 127 Rumah Aman yang tersedia secara nasional untuk jutaan korban potensial. Waktu pemrosesan laporan KDRT rata-rata 8-14 bulan, dan hanya 18% kasus yang berujung vonis. Kasus Baiq Nuril yang viral menunjukkan betapa sistem hukum Indonesia masih bias gender.
Program pelatihan sensitivitas gender untuk aparat penegak hukum baru mencakup 23% dari target. Banyak korban justru disalahkan atau diminta “berdamai” dengan pelaku oleh mediator yang tidak terlatih. Anggaran untuk penanganan KBG hanya 0,03% dari APBN—tidak sebanding dengan skala masalah.
Survei UNFPA 2024 menemukan 1 dari 4 perempuan muda Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual sebelum usia 25 tahun, namun edukasi consent dan healthy relationship hampir tidak ada dalam kurikulum pendidikan nasional. RUU TPKS yang diharapkan jadi game-changer terkendala implementasi di daerah—70% provinsi belum punya Perda turunan.
Baca Juga Solusi untuk Masa Depan
Saatnya Suara Gen Z Didengar
Tujuh masalah sosial yang diabaikan pemerintah di atas—dari kesehatan mental, pendidikan, lapangan kerja, perumahan, akses kesehatan, polusi udara, hingga kekerasan gender—adalah isu yang langsung berdampak pada kehidupan Gen Z. Data menunjukkan bahwa tanpa intervensi konkret dan terukur, masalah-masalah ini akan terus memburuk dan menciptakan generasi yang tertinggal.
Kabar baiknya, Gen Z punya suara dan tools untuk mengadvokasi perubahan. Gunakan media sosial untuk awareness, dukung NGO yang bekerja di isu-isu ini, dan yang terpenting: jangan apatis terhadap proses politik. Perubahan sistemik dimulai dari pemilih muda yang informed dan kritis.
Pertanyaan untuk kamu: Dari 7 poin di atas, mana yang paling kamu rasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Bagikan pengalaman kamu di kolom komentar—data dan cerita nyata dari masyarakat akan memperkuat advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih pro-rakyat! 🚀