semdinlihaber.com, 1 mei 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88
Dekade 1980-an merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia, ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat di bawah rezim Orde Baru, namun juga diwarnai oleh berbagai masalah sosial yang kompleks. Meskipun pemerintah saat itu berfokus pada pembangunan ekonomi melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan konflik budaya menjadi isu yang terus mengemuka. Masalah sosial pada periode ini tidak hanya mencerminkan tantangan internal masyarakat Indonesia, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika global, seperti globalisasi dan perkembangan teknologi.
Artikel ini akan menguraikan secara rinci masalah sosial yang menonjol di Indonesia pada tahun 1980-an, faktor penyebabnya, dampaknya terhadap masyarakat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Dengan pendekatan yang sistematis, artikel ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi sosial pada dekade tersebut.
Konteks Sejarah dan Sosial Tahun 1980-an

Pada tahun 1980-an, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dalam kerangka Orde Baru, yang menitikberatkan pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Program pembangunan nasional, seperti peningkatan produksi pangan melalui revolusi hijau dan industrialisasi, berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik kemajuan ekonomi, terdapat masalah sosial yang mengakar, seperti kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dan ketegangan sosial akibat kebijakan pemerintah yang sentralistik.
Selain itu, globalisasi mulai memengaruhi Indonesia melalui masuknya budaya Barat, media massa, dan teknologi. Hal ini menciptakan perubahan sosial yang cepat, tetapi juga memunculkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan modern. Urbanisasi yang meningkat juga menyebabkan tekanan pada infrastruktur perkotaan dan memperburuk masalah sosial seperti pengangguran dan kriminalitas.
Masalah Sosial Utama di Tahun 1980-an 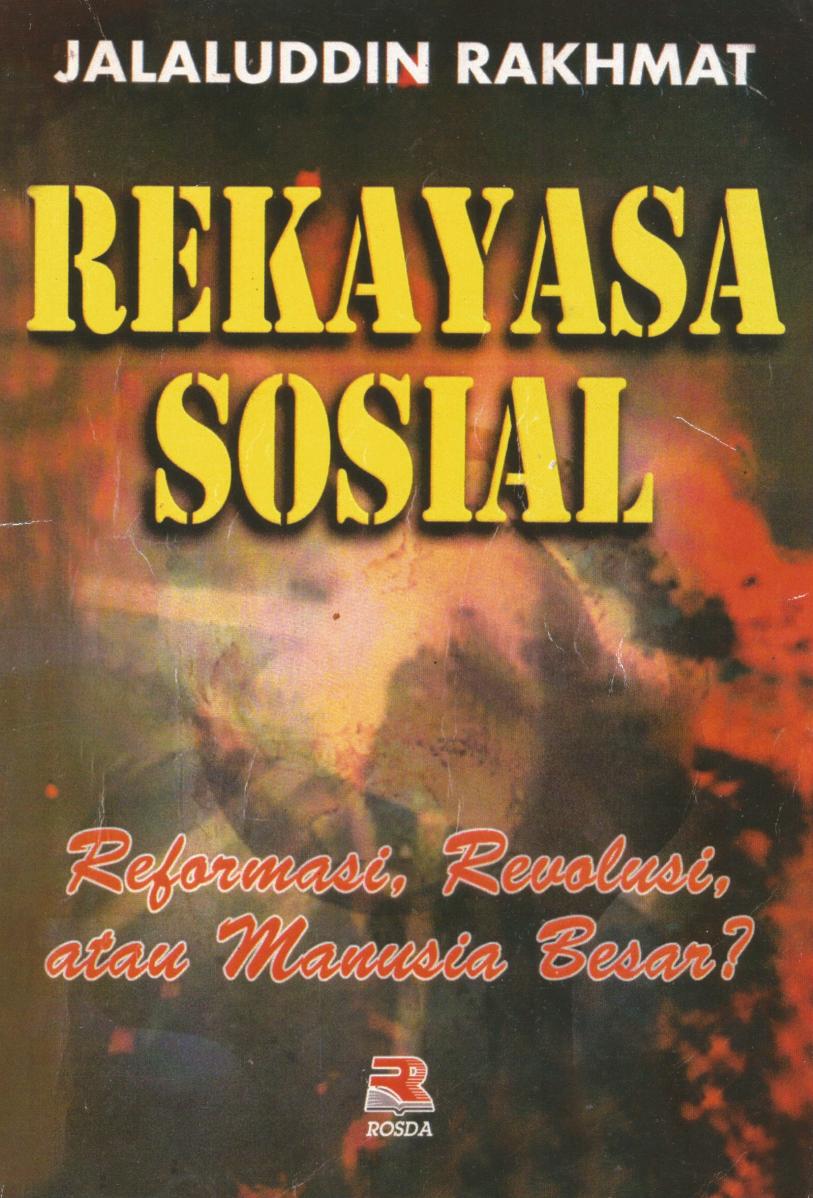
Berikut adalah masalah sosial utama yang dihadapi Indonesia pada dekade 1980-an, beserta analisis mendalam tentang penyebab dan dampaknya:
1. Kemiskinan 
Kemiskinan tetap menjadi masalah sosial yang signifikan di Indonesia selama tahun 1980-an. Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan angka kemiskinan dibandingkan dekade sebelumnya, jutaan penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan ini terbagi menjadi dua jenis: kemiskinan alamiah (akibat keterbatasan sumber daya alam atau bencana alam) dan kemiskinan buatan (akibat ketimpangan distribusi sumber daya).
Penyebab:
-
Ketimpangan Ekonomi: Pembangunan ekonomi yang berfokus pada sektor perkotaan dan industri menyebabkan kesenjangan antara kota dan desa. Wilayah pedesaan, yang mayoritas penduduknya bergantung pada pertanian, sering kali tidak mendapatkan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi.
-
Akses Terbatas ke Pendidikan dan Kesehatan: Banyak keluarga miskin tidak mampu mengakses pendidikan berkualitas atau layanan kesehatan, yang memperburuk siklus kemiskinan.
-
Struktur Sosial: Kemiskinan struktural, di mana kelompok masyarakat tertentu terjebak dalam kondisi miskin karena sistem sosial-ekonomi, menjadi tantangan besar.
Dampak:
-
Rendahnya kualitas hidup, termasuk gizi buruk dan tingginya angka kematian bayi.
-
Meningkatnya ketergantungan pada bantuan sosial, yang sering kali tidak memadai.
-
Munculnya masalah sosial lain, seperti kriminalitas dan kenakalan remaja, akibat tekanan ekonomi.
Contoh Kasus: Pada awal 1980-an, banyak petani di pedesaan Jawa menghadapi kesulitan ekonomi akibat fluktuasi harga hasil pertanian dan keterbatasan lahan. Hal ini mendorong migrasi ke kota, yang memperburuk masalah kemiskinan perkotaan.
2. Pengangguran 
Pengangguran menjadi masalah sosial yang menonjol, terutama di kalangan pemuda dan lulusan sekolah menengah. Pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, terutama di sektor formal.
Penyebab:
-
Ketidaksesuaian Keterampilan: Sistem pendidikan pada saat itu belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga banyak lulusan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri.
-
Urbanisasi Cepat: Migrasi besar-besaran dari desa ke kota menyebabkan oversupply tenaga kerja di perkotaan, terutama untuk pekerjaan informal.
-
Keterbatasan Investasi: Sektor industri yang sedang berkembang belum mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Dampak:
-
Meningkatnya angka kriminalitas, seperti pencurian dan penjarahan, sebagai akibat dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup.
-
Rendahnya produktivitas masyarakat, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
-
Frustrasi sosial, terutama di kalangan pemuda, yang merasa tidak memiliki peluang untuk maju.
Contoh Kasus: Di Jakarta, banyak pemuda yang bermigrasi dari pedesaan berakhir sebagai pekerja informal, seperti pedagang kaki lima atau buruh harian, dengan pendapatan yang tidak menentu.
3. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi 
Kesenjangan sosial-ekonomi antara kelompok masyarakat semakin terlihat jelas pada tahun 1980-an. Sementara segelintir elit menikmati hasil pembangunan, mayoritas penduduk tetap hidup dalam kondisi sulit.
Penyebab:
-
Kebijakan Ekonomi Sentralistik: Pembangunan terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar, meninggalkan wilayah lain, seperti Indonesia Timur, dalam kondisi tertinggal.
-
Korupsi dan Nepotisme: Praktik korupsi dan kolusi tautan pada elit politik dan bisnis memperburuk distribusi kekayaan yang tidak merata.
-
Globalisasi: Masuknya investasi asing dan perusahaan multinasional menciptakan peluang ekonomi bagi kelompok tertentu, tetapi tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat.
Dampak:
-
Ketegangan sosial antara kelompok masyarakat, terutama antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.
-
Munculnya sentimen terhadap kelompok tertentu, seperti etnis Tionghoa, yang sering dikaitkan dengan kesuksesan ekonomi.
-
Ketidakpuasan terhadap pemerintah, yang menjadi benih demonstrasi mahasiswa pada akhir 1980-an.
Contoh Kasus: Kesenjangan ekonomi terlihat jelas di Jakarta, di mana pemukiman mewah berdampingan dengan kawasan kumuh, seperti di sepanjang sungai Ciliwung.
4. Kriminalitas 
Tingkat kriminalitas meningkat pada tahun 1980-an, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Pencurian, perampokan, dan kekerasan menjadi masalah sosial yang mengkhawatirkan.
Penyebab:
-
Kemiskinan dan Pengangguran: Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar mendorong sebagian masyarakat melakukan tindakan kriminal.
-
Urbanisasi: Pertumbuhan kota yang tidak terkendali menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kejahatan, seperti pemukiman kumuh.
-
Lemahnya Penegakan Hukum: Sistem kepolisian pada saat itu sering kali tidak efektif dalam menangani kejahatan, dan korupsi di kalangan aparat memperburuk situasi.
Dampak:
-
Rasa tidak aman di kalangan masyarakat, terutama di malam hari.
-
Penurunan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
-
Trauma psikologis bagi korban kejahatan.
Contoh Kasus: Pada tahun 1987, terjadi peristiwa tragis Tragedi Bintaro, sebuah tabrakan kereta api yang menewaskan 156 orang. Meskipun bukan kejahatan langsung, insiden ini memicu diskusi tentang kelalaian dan korupsi dalam sistem transportasi, yang memperburuk persepsi terhadap keamanan publik.
5. Konflik Sosial dan Budaya

Perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi dan modernisasi memicu konflik antara nilai-nilai tradisional dan modern. Selain itu, kebijakan pemerintah yang menekan kebebasan berekspresi juga memicu ketegangan sosial.
Penyebab:
-
Globalisasi Budaya: Masuknya budaya Barat melalui media, seperti MTV dan film Hollywood, memengaruhi gaya hidup pemuda, yang sering dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal.
-
Kebijakan Represif: Pemerintah Orde Baru menerapkan kontrol ketat terhadap media, organisasi sosial, dan kebebasan berpendapat, yang memicu ketidakpuasan di kalangan mahasiswa dan intelektual.
-
Ketegangan Etnis dan Agama: Meskipun tidak seintens dekade berikutnya, ketegangan antara kelompok etnis dan agama mulai muncul, terutama di daerah perkotaan.
Dampak:
-
Munculnya gerakan bawah tanah, seperti Lambda Indonesia (organisasi gay pertama di Indonesia, didirikan pada 1982), sebagai respons terhadap represi sosial.
-
Demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi demokrasi, meskipun masih dalam skala kecil.
-
Ketegangan dalam komunitas lokal akibat perubahan nilai-nilai budaya.
Contoh Kasus: Pada tahun 1981, pembajakan pesawat Garuda Indonesia Penerbangan 206 oleh kelompok ekstremis Komando Jihad menunjukkan adanya ketegangan sosial dan politik yang berakar pada ketidakpuasan terhadap pemerintah.
6. Pendidikan dan Kesenjangan Akses 
Meskipun pemerintah meluncurkan program wajib belajar pada tahun 1984, akses pendidikan tetap menjadi masalah sosial, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.
Penyebab:
-
Keterbatasan Infrastruktur: Banyak daerah tidak memiliki sekolah yang memadai, dan tenaga pengajar sering kali kurang berkualitas.
-
Biaya Pendidikan: Meskipun wajib belajar dicanangkan, biaya seragam, buku, dan transportasi masih menjadi beban bagi keluarga miskin.
-
Fokus pada Kuantitas: Program pemerintah lebih menekankan pada peningkatan jumlah siswa daripada kualitas pendidikan.
Dampak:
-
Tingginya angka putus sekolah, terutama di kalangan anak-anak dari keluarga miskin.
-
Rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.
-
Meningkatnya kesenjangan sosial antara mereka yang berpendidikan dan yang tidak.
Contoh Kasus: Di daerah seperti Kalimantan dan Papua, banyak anak-anak harus berjalan jauh atau menyeberang sungai untuk sampai ke sekolah, yang sering kali hanya memiliki fasilitas minim.
Faktor Penyebab Masalah Sosial di Tahun 1980-an
Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial timbul akibat ketidaksesuaian antara nilai-nilai masyarakat dan realitas yang ada. Berikut adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan masalah sosial pada periode ini:
-
Faktor Ekonomi:
-
Ketimpangan distribusi sumber daya dan kekayaan.
-
Krisis ekonomi global pada awal 1980-an, yang memengaruhi harga komoditas ekspor seperti minyak.
-
Urbanisasi yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja.
-
-
Faktor Budaya:
-
Konflik antara nilai tradisional dan modern akibat globalisasi.
-
Heterogenitas masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, memicu potensi konflik.
-
Perubahan pola perilaku, seperti meningkatnya kenakalan remaja dan pergaulan bebas.
-
-
Faktor Politik:
-
Kebijakan sentralistik Orde Baru yang membatasi partisipasi masyarakat.
-
Korupsi dan nepotisme di kalangan pejabat, yang memperburuk kepercayaan publik.
-
Represi terhadap kebebasan berekspresi, yang memicu ketegangan sosial.
-
-
Faktor Sosial:
-
Urbanisasi yang cepat menyebabkan tekanan pada infrastruktur dan layanan publik.
-
Kesenjangan sosial antara kelompok etnis, agama, dan kelas ekonomi.
-
Lemahnya lembaga sosial, seperti keluarga, dalam menghadapi perubahan sosial.
-
Upaya Penanganan Masalah Sosial
Pemerintah Orde Baru dan masyarakat melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah sosial pada tahun 1980-an, meskipun hasilnya bervariasi:
-
Program Pembangunan:
-
Revolusi Hijau: Meningkatkan produksi pangan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan.
-
Transmigrasi: Memindahkan penduduk dari daerah padat seperti Jawa ke daerah lain untuk mengurangi tekanan ekonomi dan sosial.
-
Inpres Desa Tertinggal: Program untuk meningkatkan infrastruktur di desa-desa miskin.
-
-
Kebijakan Pendidikan:
-
Program wajib belajar 6 tahun untuk meningkatkan akses pendidikan dasar.
-
Pembangunan sekolah-sekolah baru di daerah terpencil.
-
-
Penegakan Hukum:
-
Operasi keamanan untuk menekan kriminalitas, meskipun sering kali kontroversial karena pelanggaran HAM.
-
Pembentukan pos-pos keamanan lingkungan (Poskamling) untuk meningkatkan keamanan lokal.
-
-
Inisiatif Masyarakat:
-
Munculnya organisasi sosial, seperti organisasi keagamaan dan kelompok pemuda, untuk mengatasi masalah lokal.
-
Kegiatan gotong royong untuk memperbaiki infrastruktur komunal, seperti saluran air dan jalan.
-
Namun, banyak dari upaya ini tidak sepenuhnya efektif karena faktor seperti korupsi, birokrasi yang lambat, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Misalnya, program transmigrasi sering kali memicu konflik dengan penduduk lokal, dan bantuan untuk desa tertinggal tidak selalu sampai ke tangan yang tepat.
Dampak Jangka Panjang
Masalah sosial di tahun 1980-an memiliki dampak jangka panjang terhadap masyarakat Indonesia:
-
Krisis Ekonomi 1997-1998: Kesenjangan ekonomi dan korupsi yang tidak terselesaikan menjadi salah satu pemicu krisis moneter pada akhir 1990-an.
-
Reformasi 1998: Ketidakpuasan sosial terhadap Orde Baru memuncak dalam gerakan mahasiswa yang menggulingkan Soeharto.
-
Konflik Sosial: Ketegangan etnis dan agama yang mulai muncul pada 1980-an meningkat pada dekade berikutnya, seperti konflik di Ambon dan Poso.
-
Perubahan Budaya: Globalisasi budaya pada 1980-an membentuk identitas generasi muda yang lebih terbuka, tetapi juga memicu perdebatan tentang nilai-nilai nasional.
Kesimpulan
Tahun 1980-an adalah periode yang penuh kontradiksi di Indonesia. Di satu sisi, dekade ini menyaksikan kemajuan ekonomi dan modernisasi, tetapi di sisi lain, masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, kriminalitas, dan konflik budaya menjadi tantangan besar. Faktor ekonomi, budaya, politik, dan sosial saling berkaitan dalam menciptakan dinamika yang kompleks. Meskipun pemerintah dan masyarakat berupaya mengatasi masalah ini, banyak isu tetap berlanjut hingga dekade berikutnya, membentuk arah perkembangan sosial dan politik Indonesia.
Masalah sosial pada tahun 1980-an mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi saja tidak cukup tanpa disertai dengan keadilan sosial, pemerataan, dan partisipasi masyarakat. Dengan memahami tantangan masa lalu, kita dapat mengambil pelajaran untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis di masa depan.
BACA JUGA: Munculnya Robot Teknologi AI dan Perkembangannya di Tahun 2045
BACA JUGA: Sejarah dan Perjalanan BTS: Fenomena K-Pop Global
BACA JUGA: Sejarah dan Perjalanan Eminem: Ikon Hip-Hop Global
