semdinlihaber.com, 02 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88
Pada abad ke-18, khususnya sekitar tahun 1710-an, wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia—saat itu disebut Nusantara atau Hindia Belanda—berada di bawah kekuasaan kolonial Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC). Periode ini ditandai dengan berbagai masalah sosial yang muncul akibat eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dan perubahan struktur sosial yang diterapkan oleh VOC. Artikel ini akan mengulas secara mendetail masalah sosial yang terjadi di Indonesia pada tahun 1710-an, dengan fokus pada dampak kolonialisme VOC, konflik sosial, ketimpangan ekonomi, pemberontakan, dan pengaruh budaya asing, berdasarkan sumber-sumber sejarah yang terpercaya.
1. Latar Belakang: Kolonialisme VOC di Nusantara

Pada awal abad ke-17, VOC mendapatkan hak monopoli perdagangan dan aktivitas kolonial di Nusantara melalui piagam dari Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markas utama VOC berada di Batavia (kini Jakarta), yang menjadi pusat administrasi dan perdagangan. Pada tahun 1710-an, VOC telah menguasai berbagai wilayah strategis di Nusantara, termasuk Maluku, Jawa, Banten, Makassar, dan sebagian Sumatra, dengan fokus utama pada monopoli perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada.
Namun, di balik keberhasilan ekonomi VOC, terdapat masalah sosial yang signifikan. VOC tidak hanya bertindak sebagai perusahaan dagang, tetapi juga sebagai kekuatan politik dan militer yang memaksakan kehendaknya melalui kekerasan, perjanjian paksa, dan eksploitasi sumber daya. Periode 1683–1710, sebagaimana dicatat dalam sumber sejarah, merupakan masa ketika VOC mengalami masalah keuangan yang berat akibat korupsi internal, pengeluaran tidak efisien, dan pemberontakan lokal, yang memperparah ketegangan sosial di masyarakat pribumi.
2. Masalah Sosial Utama di Indonesia pada Tahun 1710-an 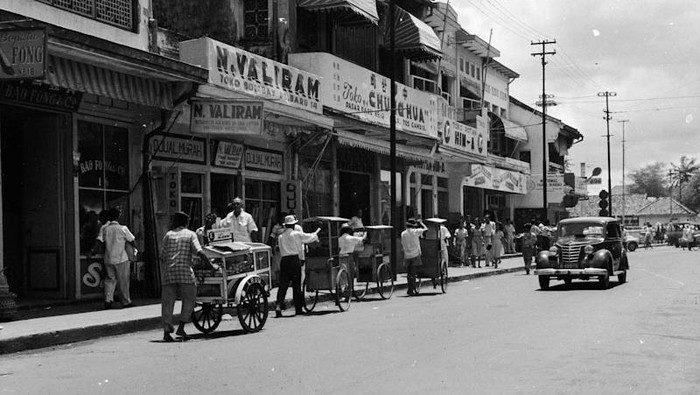
2.1. Eksploitasi Ekonomi dan Ketimpangan Sosial
Salah satu masalah sosial terbesar pada periode ini adalah eksploitasi ekonomi yang dilakukan VOC terhadap penduduk pribumi. VOC memaksakan sistem tanam paksa (meskipun istilah ini lebih dikenal pada abad ke-19, praktik serupa sudah diterapkan pada abad ke-18) dan pengenaan pajak berat untuk memastikan pasokan rempah-rempah dan komoditas lain seperti kopi dan tebu. Di Jawa, misalnya, VOC menuntut hasil bumi seperti beras dan lada dari petani tanpa kompensasi yang adil, menyebabkan kemiskinan meluas di kalangan masyarakat agraris.
-
Pajak dan Upeti: Penduduk pribumi, terutama di wilayah pesisir Jawa, Banten, dan Cirebon, diwajibkan membayar upeti dalam bentuk hasil bumi atau tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan banyak petani kehilangan sumber penghidupan mereka, memperdalam kesenjangan sosial antara elite pribumi yang bekerja sama dengan VOC dan rakyat jelata.
-
Perbudakan dan Kerja Paksa: VOC mempekerjakan budak dan buruh paksa, baik pribumi maupun yang didatangkan dari wilayah lain, untuk bekerja di perkebunan dan pelabuhan. Contohnya, di Kepulauan Banda, VOC melakukan genosida terhadap penduduk lokal pada awal abad ke-17 untuk mengamankan monopoli pala, dan pada 1710-an, wilayah ini dihuni oleh budak yang bekerja di bawah kondisi tidak manusiawi.
Ketimpangan ini memicu keresahan sosial, karena banyak masyarakat pribumi merasa dirampas haknya atas tanah dan hasil bumi mereka. Sementara itu, elite pribumi seperti bupati yang berkolaborasi dengan VOC sering mendapatkan keuntungan, menciptakan pelapisan sosial baru di mana golongan Eropa berada di puncak, diikuti oleh golongan Timur Asing (seperti Tionghoa), dan pribumi di posisi terendah.
2.2. Penindasan Politik dan Hilangnya Otonomi Pribumi 
VOC tidak hanya mengendalikan ekonomi, tetapi juga campur tangan dalam urusan politik lokal. Pada 1710-an, kekuasaan penguasa pribumi seperti sultan dan bupati semakin terbatas karena intervensi VOC dalam urusan istana, seperti pergantian tahta dan pengangkatan pejabat. Hal ini menyebabkan hilangnya otonomi politik dan meningkatkan ketegangan sosial.
-
Intervensi dalam Pemerintahan Lokal: Di Jawa, VOC memanfaatkan konflik internal kerajaan seperti Kesultanan Mataram untuk memperkuat pengaruhnya. Misalnya, setelah Perang Suksesi Jawa (1704–1719), VOC mendukung pihak tertentu untuk memastikan kendali atas wilayah strategis seperti pesisir Jawa. Akibatnya, banyak penguasa lokal kehilangan kekuasaan, dan rakyat merasa semakin terasing dari pemerintahan mereka sendiri.
-
Aneksasi Wilayah: Aneksasi wilayah oleh VOC, seperti di Banten dan Cirebon, menyebabkan menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi, yang pada gilirannya mengurangi sumber pendapatan seperti lungguh (tanah jabatan) dan upeti. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan bangsawan pribumi, yang sering kali melimpahkan beban ekonomi ke rakyat jelata, memperburuk kondisi sosial.
2.3. Pemberontakan dan Konflik Sosial
Keresahan akibat eksploitasi dan penindasan memicu pemberontakan di berbagai wilayah pada 1710-an. Pemberontakan ini merupakan respons terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi yang diterapkan VOC.
-
Pemberontakan di Jawa: Salah satu contoh signifikan adalah pemberontakan yang dipimpin oleh bangsawan lokal di Jawa akibat tekanan ekonomi VOC. Pada 1710-an, VOC menghadapi pemberontakan berkelanjutan di wilayah pesisir Jawa, seperti Cirebon dan Banten, karena penduduk menolak pajak berat dan kerja paksa. Pemberontakan ini sering kali melibatkan rakyat jelata yang menderita akibat kemiskinan dan penindasan.
-
Konflik dengan Komunitas Tionghoa: Di Batavia, komunitas Tionghoa yang menjadi perantara perdagangan VOC sering menjadi sasaran kecemburuan sosial. Pada 1740 (di luar periode 1710-an, tetapi menunjukkan pola ketegangan), terjadi pembantaian Tionghoa di Batavia akibat ketegangan sosial dan ekonomi. Pada 1710-an, ketegangan serupa sudah mulai muncul karena komunitas Tionghoa dianggap mendapatkan keistimewaan dari VOC dibandingkan pribumi.
2.4. Pengaruh Budaya Asing dan Perubahan Sosial 
Kedatangan VOC membawa pengaruh budaya Eropa yang memengaruhi struktur sosial masyarakat pribumi. Namun, fokus utama VOC adalah eksploitasi ekonomi, sehingga kebijakan sosial dan budaya mereka cenderung terbatas dan mendukung kepentingan kolonial.
-
Penyebaran Agama Kristen: VOC memperkenalkan agama Kristen Protestan melalui organisasi seperti Nederlands Zendeling Genootschap (NZG), meskipun upaya misionaris pada 1710-an masih terbatas dibandingkan abad ke-19. Penyebaran agama ini menciptakan ketegangan dengan masyarakat pribumi yang mayoritas beragama Islam atau Hindu-Buddha, terutama di wilayah seperti Maluku dan Jawa.
-
Perubahan Tradisi Lokal: Tradisi istana pribumi, seperti upacara kerajaan, mulai disederhanakan atau dihilangkan karena pengaruh Belanda. Misalnya, di Jawa, tata cara kerajaan Mataram mulai digantikan dengan sistem administrasi kolonial, yang mengurangi nilai budaya lokal dan memicu perasaan kehilangan identitas di kalangan pribumi.
-
Feodalisme Baru: Kebijakan VOC yang memaksa penduduk tunduk pada tuan tanah Eropa atau Timur Asing (seperti Tionghoa) menciptakan budaya feodalisme baru. Hal ini berbeda dari feodalisme tradisional Jawa yang berbasis pada hubungan sosial dan budaya, dan lebih berorientasi pada eksploitasi ekonomi, menyebabkan kemerosotan kehidupan sosial masyarakat pedesaan.
2.5. Korupsi dan Kebejatan Moral dalam VOC
Masalah sosial tidak hanya terjadi di kalangan pribumi, tetapi juga di dalam administrasi VOC. Pada 1710-an, VOC menghadapi krisis keuangan akibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabatnya. Salah satu kasus terkenal adalah setelah kematian Gubernur Jenderal Cornelis Speelman pada 1684, ketika terungkap bahwa ia melakukan pembayaran untuk pekerjaan fiktif menggunakan dana VOC. Meskipun kasus ini terjadi sebelum 1710-an, praktik korupsi terus berlanjut dan memengaruhi hubungan sosial antara VOC dan penduduk lokal.
Korupsi ini memperburuk eksploitasi terhadap pribumi, karena pejabat VOC sering kali memeras penduduk untuk keuntungan pribadi. Hal ini meningkatkan ketidakpercayaan dan permusuhan terhadap penguasa kolonial, yang pada gilirannya memicu konflik sosial.
3. Dampak Sosial terhadap Masyarakat Pribumi
3.1. Kemiskinan dan Penderitaan Ekonomi
Eksploitasi ekonomi VOC menyebabkan kemiskinan meluas di kalangan petani dan buruh. Banyak penduduk kehilangan tanah mereka karena diambil alih untuk perkebunan atau karena gagal membayar pajak. Di wilayah seperti Ambon dan Banda, penduduk pribumi hampir sepenuhnya digantikan oleh budak, yang hidup dalam kondisi sangat buruk.
3.2. Mobilitas Sosial Terbatas
Meskipun kolonialisme membuka peluang mobilitas sosial bagi segelintir pribumi yang menjadi pegawai VOC atau elite lokal, mayoritas penduduk tetap terjebak dalam strata sosial rendah. Munculnya golongan priyayi cendekiawan di perkotaan pada abad ke-18 merupakan fenomena awal, tetapi jumlahnya sangat terbatas dan tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan sosial yang meluas.
3.3. Isolasi dan Kemunduran Perdagangan
Kebijakan monopoli VOC mengisolasi banyak wilayah Indonesia dari perdagangan internasional, terutama di wilayah timur seperti Maluku dan Nusa Tenggara. Hal ini menyebabkan kemunduran perdagangan laut dan memaksa masyarakat lokal beralih ke ekonomi pedalaman, yang sering kali bersifat feodal dan memperburuk kondisi sosial.
4. Respon Masyarakat terhadap Masalah Sosial
4.1. Pemberontakan Lokal
Pemberontakan menjadi salah satu bentuk perlawanan utama terhadap penindasan VOC. Selain pemberontakan di Jawa, wilayah seperti Banten dan Makassar juga menyaksikan perlawanan bersenjata. Meskipun banyak pemberontakan ini gagal karena kurangnya organisasi dan persenjataan, mereka menunjukkan tingkat ketidakpuasan sosial yang tinggi.
4.2. Kolaborasi dengan VOC
Sebagian elite pribumi memilih berkolaborasi dengan VOC untuk mempertahankan status sosial mereka. Bupati di Jawa, misalnya, sering kali menjadi perantara antara VOC dan rakyat, tetapi tindakan mereka sering dipandang sebagai pengkhianatan oleh masyarakat bawah, menciptakan ketegangan sosial tambahan.
4.3. Perkembangan Awal Nasionalisme
Meskipun gagasan nasionalisme modern belum muncul pada 1710-an, ketegangan sosial akibat kolonialisme mulai menumbuhkan rasa kesadaran kolektif di kalangan pribumi, terutama di wilayah yang mengalami penindasan berat seperti Jawa dan Maluku. Ini menjadi cikal bakal pergerakan nasional yang muncul pada abad ke-19 dan ke-20.
5. Analisis dan Relevansi
Masalah sosial pada 1710-an di Indonesia mencerminkan dampak kolonialisme yang tidak hanya terbatas pada eksploitasi ekonomi, tetapi juga perubahan mendalam dalam struktur sosial, politik, dan budaya masyarakat. VOC, sebagai entitas yang lebih mengutamakan keuntungan daripada kesejahteraan penduduk, menciptakan ketimpangan yang memicu pemberontakan dan keresahan sosial. Korupsi internal VOC memperburuk situasi, karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah disalahgunakan.
Dibandingkan dengan periode sebelumnya, seperti abad ke-16 ketika kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit masih berkuasa, periode 1710-an menunjukkan penurunan otonomi sosial dan politik masyarakat pribumi. Namun, ketegangan sosial ini juga menjadi fondasi bagi perlawanan yang lebih terorganisir di masa depan, seperti Perang Jawa (1825–1830) dan gerakan nasionalis abad ke-20.
6. Tantangan dan Keterbatasan Data
Sumber sejarah tentang periode 1710-an di Indonesia terbatas, terutama karena minimnya dokumentasi dari perspektif pribumi. Sebagian besar catatan berasal dari arsip VOC, yang cenderung bias terhadap kepentingan kolonial. Selain itu, fokus VOC pada perdagangan membuat aspek sosial masyarakat pribumi kurang terekam secara mendetail. Namun, melalui analisis pemberontakan, kebijakan kolonial, dan laporan administrasi, kita dapat merekonstruksi gambaran masalah sosial pada masa itu.
7. Kesimpulan
Pada tahun 1710-an, Indonesia menghadapi berbagai masalah sosial yang berakar dari kolonialisme VOC. Eksploitasi ekonomi melalui pajak, kerja paksa, dan monopoli perdagangan menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang meluas. Penindasan politik mengurangi otonomi penguasa pribumi, sementara pengaruh budaya asing dan korupsi internal VOC memperburuk ketegangan sosial. Pemberontakan lokal menjadi cerminan keresahan masyarakat, meskipun sering kali gagal karena keterbatasan sumber daya. Periode ini menunjukkan bagaimana kolonialisme tidak hanya mengubah ekonomi, tetapi juga struktur sosial masyarakat Nusantara, meninggalkan warisan ketimpangan yang berlangsung selama berabad-abad. Dengan memahami masalah sosial pada 1710-an, kita dapat melihat akar sejarah dari tantangan sosial-ekonomi yang masih relevan hingga kini.
BACA JUGA: Panel Distribusi, Breaker, dan MCB: Fungsi, Komponen, dan Aplikasi dalam Sistem Kelistrikan
BACA JUGA: Hukum Acara (Formil): Pengertian, Prinsip, dan Penerapan di Indonesia
BACA JUGA: Badut-badut Politik: Fenomena, Dampak, dan Respons Masyarakat di Indonesia
